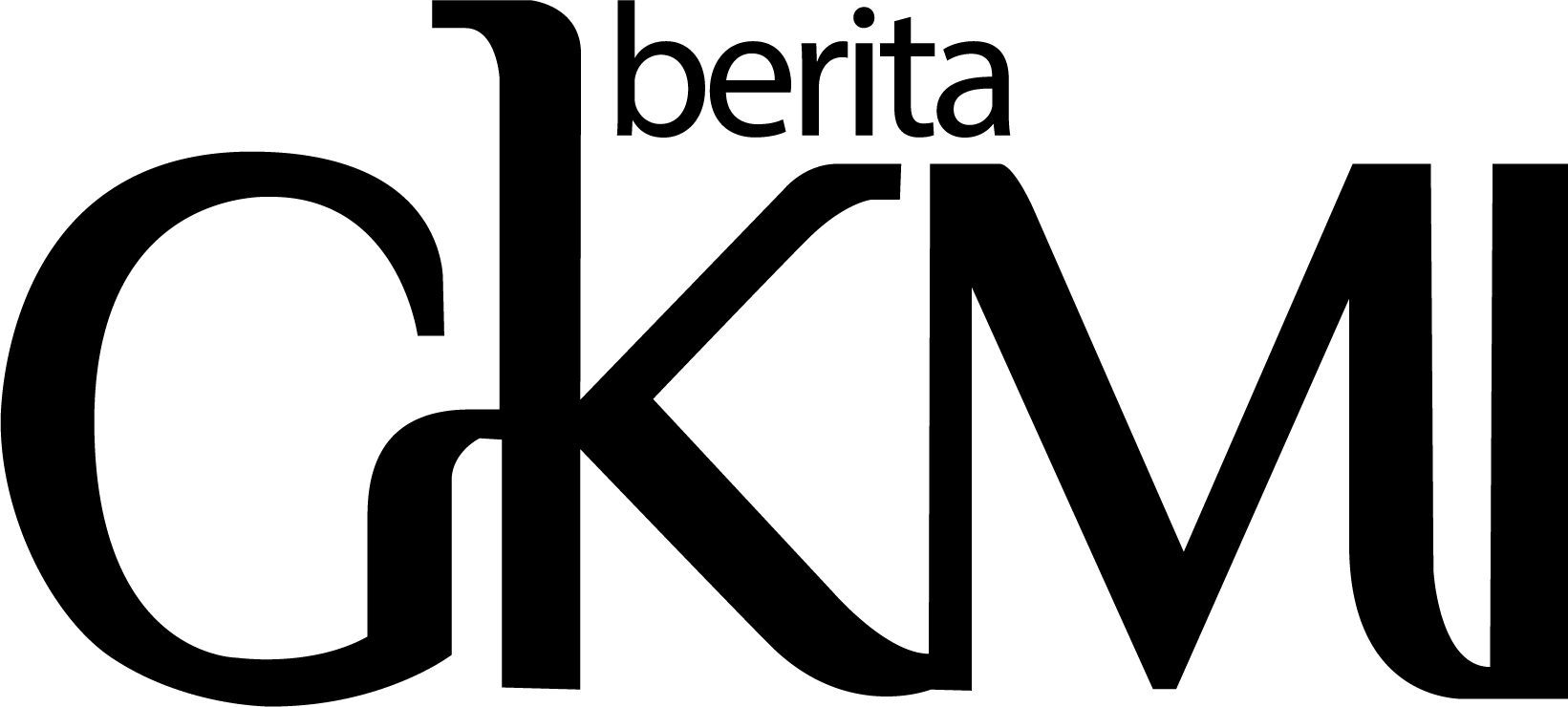Bystander Effect: Mengapa Kita juga Bisa Disebut sebagai Pelaku Bullying?
Pernahkah kita melihat aksi bullying tapi memutuskan untuk diam saja dan tidak membantu korban? Pernahkah kita merasa kasihan dengan korban bullying tetapi enggan untuk menolong karena takut akan menjadi sasaran selanjutnya? Atau pernahkah kita ingin menghentikan aksi bullying tetapi tidak tahu dengan cara apa? Tenang, kita tidak sendirian.
Menjadi korban bullying memanglah tidak menyenangkan, bahkan dampaknya bisa panjang kali lebar. Pun menjadi seorang pelaku juga seharusnya sama, setidaknya mengakui perbuatan dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang “hanya” menjadi penonton ketika aksi bullying itu terjadi? Apakah mereka merasa aman-aman saja karena berada di posisi tengah? Ataukah memang sebenarnya hanya cuek karena korban bukanlah diri mereka sendiri?
Studi psikologi berhasil menjawab pertanyaan ini. Ada sebuah fenomena yang disebut sebagai bystander effect, atau efek pengamat. Saya mengindikasikan diri sendiri sebagai salah satu bagian dari pengamat itu. Seorang “penonton” aksi bullying yang terkadang merasa kasihan dengan korban, terkadang pula ikut menikmati dengan menertawakan korban, dan terkadang menjadi terbiasa dengan pemandangan itu sehingga acuh. Lalu dengan enteng dan bangganya, saya–dan mungkin sebagian besar bystander–akan mengatakan bahwa kami bukanlah pelaku bullying. Padahal, kehadiran bystander di tengah aksi bullying ini sebetulnya meningkatkan perilaku bullying itu sendiri–menurut hasil jurnal Persepsi pada Bystander terhadap Intensitas Bullying pada Siswa SMP (Halimah et al., 2015).
Dikutip dari artikel 6 Ways Bullying Impacts Bystanders (Gordon, 2020), bystander melihat aksi bullying dan tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Selanjutnya mereka akan memonitor reaksi di sekitarnya, apakah situasi itu cukup genting, apakah ada orang lain yang akan terlebih dahulu menolong? Biasanya ketika tidak ada satu orang pun yang menolong, para bystander akan menjustifikasi diri mereka bahwa mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa-apa adalah hal yang paling tepat. Dan itu juga yang saya lakukan terhadap para korban bullying–kenal maupun tidak–di sekitar saya.
Satu peristiwa bullying terparah yang pernah terjadi di sekitar saya adalah ketika saya berada di usia SMP-SMA, kebetulan saya selalu bertemu di sekolah yang sama dengan si korban. Sebut saja dia Deni. Anaknya ramah, periang, baik, lugu dan lucu, serta tubuhnya gempal. Deni adalah sasaran bullying atau waktu itu saya pahami sebagai “korban candaan” teman-teman di angkatan kami. Saya melihat aksi mereka dan ikut tertawa, hingga lama-lama mulai terbiasa dengan perlakuan itu. Waktu itu kami belum tahu betul apa itu bullying, maklum, institusi pendidikan tahun 2010 belum se-aware sekarang ini.
Tak jarang ketika jam istirahat, Deni diajak untuk “menghibur” para pelaku dan murid-murid lain yang menonton atau sekadar lewat koridor kelas. Mulai dari tindakan usil, candaan antar teman, hingga ejekan verbal yang seringkali mengatai bentuk fisik dan bau tubuhnya, bahkan candaan yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.
Ada kalanya saya merasa tidak tega ketika candaan teman-teman sudah saya anggap melewati batas. Deni menangis, Deni berteriak, tetapi tidak ada yang menolong. Semua orang hanya melihat, tertawa, dan mencibir dirinya dengan sebutan “cengeng” atau “banci”. Saya sendiri tidak begitu dekat dengan para pelaku, sehingga saya hanya diam, tidak berani untuk menegur mereka. Apalagi jika mayoritas di antara mereka adalah anggota beberapa circle pertemanan yang cukup kuat di kalangan angkatan kami saat itu.
Rasa bersalah ketika melihat Deni berlari meninggalkan kerumunan seringkali mengusik hati saya, tetapi saya bisa apa? Saya tidak dekat dengan Deni, kami hanya saling kenal. Dan kala itu saya merasa, berteman dekat dengan Deni bukanlah sebuah keputusan yang tepat, karena akan menodai reputasi diri saya di sekolah. Jahat memang, tetapi sepertinya itu adalah solusi yang saya pegang agar terhindar dari masalah yang tidak saya inginkan selama bersekola
Mengapa orang lebih memilih menjadi seorang bystander?
Dikutip dari buku Social Psychology Eighth Edition 2018 karya Michael dan Graham Vaughan, setidaknya ada 3 poin alasan utama mengapa seseorang lebih memilih untuk menjadi seorang bystander (Astutik, gramedia.com):
1. Ketidaktahuan seseorang untuk bertindak
Bystander effect membuat seseorang berpikir bahwa dirinya tidak bertanggung jawab untuk menolong korban karena ada banyak orang yang menjadi saksi peristiwa bullying. Mereka berpikir bahwa pasti akan ada orang lain yang menolong korban. Sehingga semakin banyak orang yang menyaksikan aksi bullying, maka semakin kecil pula kemungkinan korban untuk ditolong. Berbeda jika peristiwa bullying disaksikan hanya oleh satu orang, respons untuk menolong akan cepat terstimulasi karena ia tahu bahwa hanya dirinya saja yang bisa menolong. Di sisi lain, mereka juga tidak tahu bagaimana caranya menghentikan aksi bullying dengan tepat.
2. Social blunders
Hal ini berkaitan dengan citra diri seseorang di mana mereka enggan menolong karena takut melakukan kesalahan dan dinilai banyak orang. Sehingga membuat bystander lebih memilih untuk diam dan tidak melakukan apapun. Mereka takut jika nantinya malah membuat diri sendiri malu atau memperburuk aksi bullying itu. Atau bisa saja mereka akan disasar menjadi korban bullying selanjutnya karena memilih untuk menolong dan memihak korban.
3. Social influence
Ketika seseorang memilih untuk diam dan tidak menolong, maka hal itu akan memengaruhi orang lain untuk tidak ikut menolong. Karena sebetulnya para bystander ini saling mengamati satu sama lain. Hasil penelitian Pepler dan Craig (2020) menunjukkan bahwa 85% dalam aksi bullying terdapat teman-teman korban yang hadir sebagai bystander. Sehingga ketika orang lain mengetahui bahwa teman-teman korban hanya diam saja, mereka akan cenderung enggan untuk membantu korban (Halimah et al., 2015). Dengan kata lain, yang mengenal korban saja tidak berniat untuk menolong dan menghentikan aksi bullying, apalagi yang tidak mengenal korban?
Menjadi bystander sama halnya dengan menjadi pelaku bullying?
Karena bullying adalah tentang mengintimidasi dan mengambil kontrol seseorang, hal ini memberikan rasa kuasa bagi pelaku bullying. Para pelaku menginginkan kuasa itu karena sebetulnya, jauh di dalam hati, mereka merasa lemah dan tidak berdaya. Dalam jurnalnya yang berjudul Bystanders are the Key to Stopping Bullying (2013), Sharon Padgett dan Charles E. Notar memaparkan ‘...there can be no bullying without bullies. However, they cannot be successful in their cruel deeds without the complicity of bystanders,’ (tidak akan ada perundungan tanpa pelaku perundungan. Namun, mereka tidak akan berhasil dalam melakukan perbuatan kejamnya tanpa keterlibatan para pengamat).
Pelaku bullying sangat suka jika ada penonton dalam aksi mereka, sehingga bystander–orang-orang yang menganggap diri mereka aman jika memilih untuk diam dan mengamati saja–akan menjadi kepanjangan tangan para pelaku untuk semakin menindas korban bullying. Karena jika aksi bullying ini disaksikan oleh banyak orang, maka harga diri, perasaan, dan pikiran korban akan semakin terintimidasi dan terabaikan.
Meskipun di kemudian hari, bystander yang sudah sadar tentang aksinya akan merasa bersalah dan menyesal, karena tidak tahu harus berbuat apa atau terlalu takut untuk menghentikan aksi bullying. Diam, mengamati, dan mengasihani dalam hati saja tidak akan menghentikan tindakan bullying. Mau itu orang yang kita kenal atau tidak, jika kita merasa bahwa perbuatan (bullying) itu salah, lawan! Rasa penyesalan dan bersalah karena tidak menolong, tidaklah sepadan dengan dampak yang telah para korban terima.
Hentikan diri menjadi bystander dan berlatih mengasah empati
Sekarang kita tahu bahwa aksi bullying adalah perbuatan yang salah, pun sama halnya dengan menjadi seorang bystander. Dalam hal ini, diam tidak akan menghasilkan apapun. Yang ada, pelaku semakin merasa berkuasa dan korban semakin tak berdaya. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan saling peduli. Bukankah itu yang seharusnya kita kerjakan? Bukan hanya diam saja dan membiarkan aksi itu terjadi terus-menerus.
Ada beberapa tips dari pamflet stopbullying.gov (2018) yang bisa membantu kita untuk keluar dari bystander effect. Pertama, bela dan lindungi orang yang menjadi target bullying. Kedua, gunakan candaan untuk mencairkan suasana yang mulai mengarah ke aksi bullying. Ketiga, lakukan penghentian aksi bullying secara berkelompok (sebisa mungkin tidak sendirian). Keempat, katakan secara terbuka bahwa kita keberatan dengan aksi bullying itu. Kelima, ganti topik pembicaraan jika sudah mengarah ke aksi bullying. Keenam, setuju dengan pernyataan maupun status sosial korban. Dan ketujuh, mempertanyakan perilaku bullying itu.
Masih dalam pamflet yang sama, mereka juga memberikan tips bagi para bystander untuk membantu mengatasi pasca bullying pada korban. Yaitu dengan menjangkau korban bullying secara pribadi untuk mengungkapkan dukungan atau perhatian kita. Menjangkau pelaku bullying secara pribadi untuk mengungkapkan kekhawatiran kita terhadap aksi mereka–jika kita merasa aman untuk melakukannya. Serta melaporkan aksi bullying itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan atau memiliki jabatan/kekuatan dengan harapan dapat membantu menghentikan aksi bullying: teman, orang tua, guru, dosen, atasan, Pendeta, dll.
Ingatlah bahwa menjadi seorang bystander bukanlah sesuatu yang bisa kita banggakan. Karena sadar atau tidak, bystander memiliki peran penting dalam penghentian aksi bullying dan dampak-dampak yang mengikutinya. Mulai coba untuk lakukan sesuatu dalam memutus rantai bullying, dimulai dengan menjauhkan diri dari bystander effect.