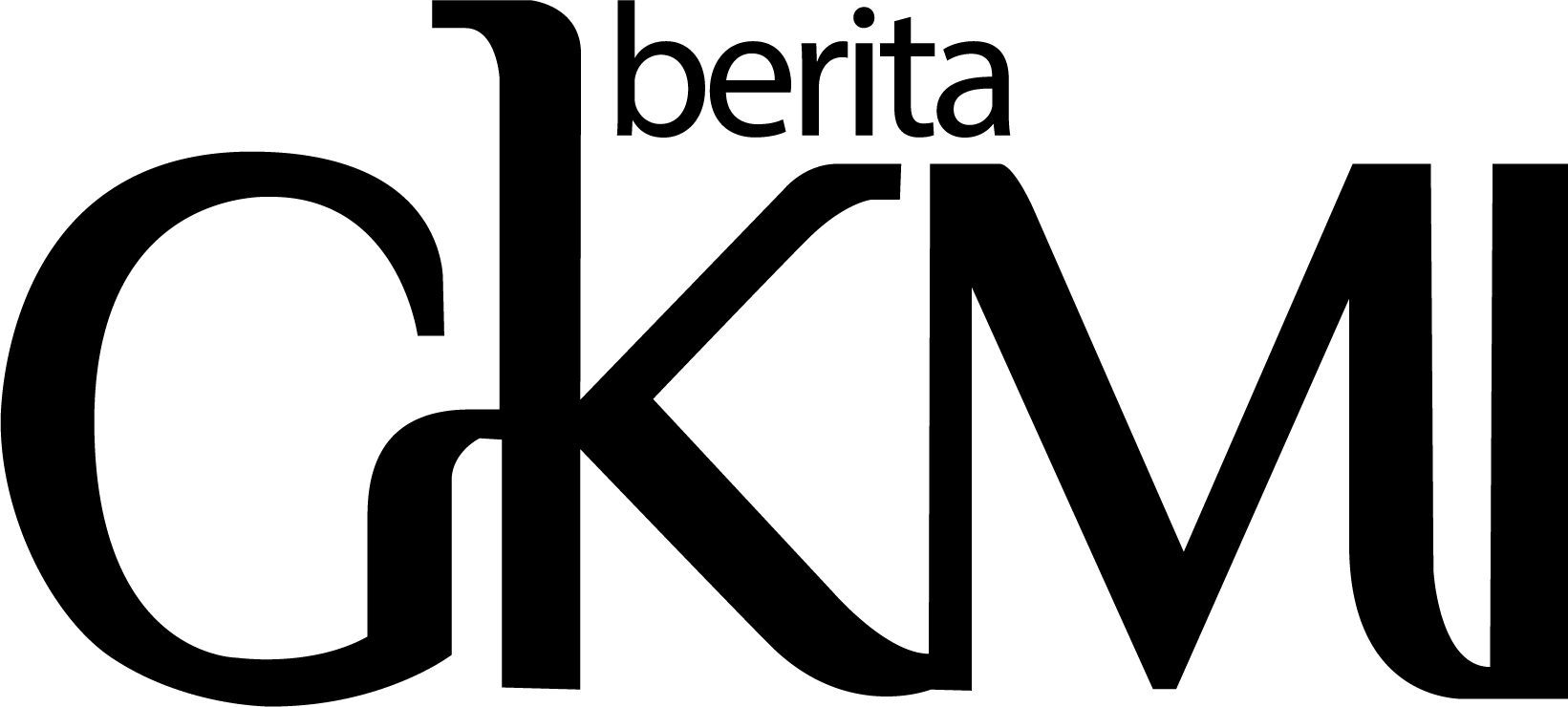Sendiri Belum Tentu Tak Berdaya
Apa yang ada di benak kita ketika mendengar tentang istilah “single parent”? Oh…janda, oh…duda, oh…kasihan ya berjuang sendiri untuk anak-anaknya. Mungkin ada dari sebagian kita yang berpikir demikian, mungkin ada juga yang memiliki kerinduan untuk menolong atau meringankan beban, mungkin ada pula yang kagum akan kehidupan para single parent ini. Saya termasuk ke kategori yang terakhir. Seringkali saya terkagum melihat kekuatan dan ketegaran para single parent dalam kembali menjalani kehidupan mereka, meski tanpa kehadiran seorang pendamping lagi di sisinya.
Istilah “life must go on”, hidup harus terus berjalan, mungkin bagi seorang single seperti saya, hal ini tak jadi masalah yang berarti, apalagi belum pernah merasakan tanggung jawab menjadi seorang parent. Tapi bagaimana dengan para parents yang kemudian menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya? “Awal saya ditinggal suami ketika masih umur 37 tahun, masih terbilang muda. Anak ada empat, yang paling besar waktu itu kelas 3 SMP. Saya harus menjalani hidup sendiri bersama dengan anak-anak, membiayai kebutuhan hidup mereka,” cerita Bu Rosalina Prayoga, salah seorang jemaat senior di GKMI Jepara. Tak hanya ekonomi, mereka juga harus menanggung tantangan psikis dan sosial. Baik sebagai perempuan maupun laki-laki. Seperti yang dialami oleh Pdt. Em. Sumihar Tambunan, “Saya sebagai duda selama 4 tahun merasakan bagaimana pergumulan hidup tanpa pendamping. Menghadapi anak-anak, mengelola keuangan keluarga, menghadapi suara masyarakat, bahkan menghadapi diri sendiri dan perjuangan move on dari situasi itu.”
Itu hanya segelintir contoh, ada tantangan-tantangan lain yang tentunya tidak kalah mengganggu para single parent. Jika terlalu bergantung pada pasangan semasa hidupnya, ketika ditinggal pun jadi harus mencari dan menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Belum juga menghadapi suara-suara di masyarakat, seperti stigma janda dan duda yang seringkali dikaitkan dengan perilaku-perilaku negatif dan belas kasihan. Ironisnya, status keduanya pun juga nampak berat sebelah di mata masyarakat, alias akan jauh lebih menderita menjadi seorang janda daripada duda. Seorang janda biasanya dianggap lemah dan haus akan kasih sayang, lebih sering dilecehkan secara seksual dan dianggap penggoda—perusak rumah tangga.
Stigma negatif seorang single parent di masyarakat
Dikutip dari id.theasianparent.com, seorang psikolog klinis, Roslina Verauli, M. Psi, memberi pernyataannya akan dampak status yang disandang oleh seorang janda, “Menyandang status janda merupakan pengalaman negatif akut bagi yang mengalaminya. Terutama di negara berkembang. Mereka sendirian dalam menghadapi berbagai masalah ekonomi, sosial, dan psikologis, antara lain: dituntut untuk mampu menafkahi diri dan anak-anaknya; menghadapi buruknya stigma sosial; kehilangan relasi dan dukungan keluarga, hilangnya perasaan diri berharga, bahkan perasaan ketakutan untuk hidup seorang diri.”
Akhir dari dilema seorang janda adalah menjadi diam dengan statusnya, diam menerima perilaku yang tidak menyenangkan dan menjadi seseorang yang tertutup. Rasanya ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, harus menghadapi tantangan pergumulan hidup sendiri maupun keluarga. Berat menyembuhkan luka yang mereka rasakan, berdiri sendiri menyandang tugas ganda: menjadi kuat untuk anak-anaknya dan menghilangkan rasa trauma kehilangan pasangan.
Mengutip dari KBBI, janda berarti wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya. Pengertian tersebut sesungguhnya tidaklah bernada negatif. Namun perempuan Indonesia yang sendirian, tanpa pendampingan dari laki-laki dianggap rentan. Saat ada pendampingan suami, pandangan terhadap perempuan menjadi lebih kuat karena ada yang melindunginya. Ini pula yang berhubungan dengan stigma “perempuan penggoda”.
Pun sebetulnya sama dengan status duda, meskipun seorang duda biasanya dianggap keren, dengan muncul istilah “duren” alias duda keren. Tetapi tetap ada stigma negatif yang turut menghiasi keberadaan mereka. “Waktu saya di Keling, istri masih ada. Saya naik motor ke arah pasar, pulangnya disetop ibu-ibu jemaat gereja, ingin nunut (ikut membonceng). Saya antar sampai ke depan rumahnya. Setelah saya jadi single parent, ibu itu selalu menolak tawaran tumpangan saya. Itu contoh perbedaan yang saya alami sebagai seorang duda kala itu,” cerita Pak Sumihar akan pengalamannya. Ternyata sama saja, seorang duda juga nampaknya bisa dilabel sebagai “penggoda” dan perusak rumah tangga.
Tapi stigma-stigma negatif itu biasanya diberatkan pada orang-orang yang telah bercerai. Sedangkan bagi orang-orang yang ditinggal mati pasangannya, biasanya lebih dominan kepada rasa belas kasihan, “Kasihan ya…ditinggal mati pasangannya. Sekarang apa-apa jadi sendirian.” Karena sesungguhnya tidak ada orang yang ingin menjadi janda atau duda dalam sebuah pernikahan. Keduanya ingin menua bersama hingga nanti Tuhan panggil secara alami di masa tuanya.
Menjadi single parent yang berdaya
“Single parent itu suatu status yang harus kita terima, tetapi tentu ada perubahan-perubahan dalam diri kita setelah ditinggal pasangan. Makanya saya ingin menggerakkan jemaat-jemaat di PGMW 4 untuk membentuk sebuah asosiasi, guna menghilangkan image negatif itu (baik bagi diri sendiri maupun masyarakat),” terang Pak Sumihar. Pengalaman pribadinya ini menjadi motivasi utama bagi dirinya untuk memotori semangat pergerakan berdirinya Komisi Single Parent (SP) di lingkup PGMW 4. Karena sesungguhnya, persekutuan yang saling menguatkan antar single parent adalah sebuah media penguatan yang tidak kita sadari atau bahkan pandang sebelah mata.
Tanggal 29 Februari 2016 menjadi saksi didirikannya komisi ini. Mulai dari tingkat PGMW 4, hingga menjadi tersebar di gereja lokal masing-masing: GKMI Welahan, GKMI Pecangaan, GKMI Jepara, GKMI Mlonggo, GKMI Krasak, GKMI Bangsri, dan GKMI Keling, dengan anggota terbanyak ada di GKMI Jepara. “Jumlah anggota paling banyak ada di GKMI Jepara, sekarang sekitar 50-an orang. Makanya single parent Jepara ‘Dorkas’ jadi persekutuan pertama, sebelum diikuti oleh gereja lokal yang lain,” jelas Bu Rosa, yang tak hanya sebagai jemaat senior di GKMI Jepara, tetapi juga anggota persekutuan SP Dorkas, sekaligus ketua Komisi SP PGMW 4. “Anggota Komisi SP isinya perempuan semua, usia antara 40-80an. Jumlah anggotanya kurang lebih 130-an. Ada juga single parent yang laki-laki, tapi untuk sekarang jumlahnya sangat sedikit dan belum mau terlibat lebih jauh di persekutuan,” lanjutnya.
Biasanya proses “perangkulan” anggota persekutuan SP dilakukan setelah seorang jemaat kehilangan pasangannya. Anggota SP lokal langsung mengunjungi jemaat tersebut, dirangkul dan diajak bergabung ke persekutuan–sebagai bagian dari dukungan dan perhatian terhadap sesama mereka. “Anggota sekarang mayoritas usianya 50 tahun ke atas, jadi mereka merasa senang ketika bisa kumpul dan pergi bareng anggota lain, apalagi kan anak-anaknya sudah dewasa dan mandiri. Daripada merenung sendirian di rumah, kita tampung supaya ga merasa sepi sendiri lagi,” lanjut Bu Rosa.
Tujuan dihimpunnya komisi ini juga sebagai payung bagi gereja-gereja lokal untuk mengadakan persekutuan SP-nya masing-masing. Persekutuan yang saling mengakrabkan, menyemangati, memotivasi, menghibur, dan tentunya menguatkan iman dan pengharapan dalam Tuhan. Setiap bulannya, SP gereja lokal mengadakan persekutuan, dan dua kali dalam setahun Komisi SP mengadakan persekutuan gabungan. Acaranya berupa ibadah persekutuan bersama, mengundang pembicara, makan bersama, kesaksian, pembagian hadiah ulang tahun, dan permainan berhadiah. Meski harus membayar kontribusi ketika datang, anggota SP tetap semangat dan senang hati mengikuti. “Kebersamaan ini membuat kita bersukacita,” kesan Bu Rosa, tidak sabar untuk mengikuti persekutuan SP gabungan 23 Mei di GKMI Pecangaan.
Topik bahasan dalam persekutuan pun tidak jauh dari bagaimana cara agar para single parent kuat menghadapi realita, mampu melanjutkan hidup meski tanpa pasangan di sisinya lagi, menjadi single parent yang mandiri, bahwa Tuhan berkarya menolong dan tidak meninggalkan mereka, bagaimana para single parent masih tetap bisa berkarya dan menjadi berkat dalam hidupnya. Bahkan tak jarang bagi SP Dorkas untuk mengadakan piknik sekaligus berbagi kasih ke kota-kota sekitar Jepara. “Kita percaya, bersama Tuhan kita bisa menjalani sampai hari ini. Ga terlalu minder atau malu lagi dilihatin orang, karena ada teman sepenanggungan. Walaupun single, tapi kita juga bisa berbagi. Ini berkat Tuhan, bahwa Tuhan tetap pelihara kita yang single,” kata Bu Rosa melanjutkan. Bahkan sangat jarang ada anggota SP yang menikah lagi karena mereka sudah merasa cukup dengan keberadaan satu sama lain.
Seperti yang dirasakan oleh salah satu anggota SP dari GKMI Keling. Ibu Nani merasa sangat terberkati oleh keberadaan komisi ini, “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih mendapat wadah Komisi SP di PGMW 4. Kami bisa bertumbuh bersama dengan teman-teman single parent di gereja kami, memuji Tuhan dan mendengar Firman Tuhan, sharing, dan berbagi makanan. Terlebih kami juga sangat terberkati dengan kegiatan tahunan Komisi SP, bisa bertemu dengan anggota single parent dari gereja lain, sharing, dan bercanda ria sehingga menguatkan kami.”
Sebagai satu-satunya Komisi Single Parent di tingkat Sinodal, PGMW 4 pun tentu berharap bisa menginspirasi PGMW-PGMW lainnya untuk turut membentuk komisi ini, sebagai salah satu bentuk kepedulian akan para jemaat single parent. Oleh karenanya, Pak Sumihar menitipkan sebuah pesan, “Sangat penting untuk menguatkan para single parent. Saya sebagai duda selama 4 tahun merasakan bagaimana pergumulan hidup tanpa pendamping. Sehingga keberadaan persekutuan/komisi ini diharapkan mampu untuk meneguhkan dan menguatkan satu dengan yang lain,” yang tentunya dapat menjadi perenungan kita bersama akan pentingnya memberi kasih dan perhatian kepada sesama, terkhusus kepada mereka, sang single parent.